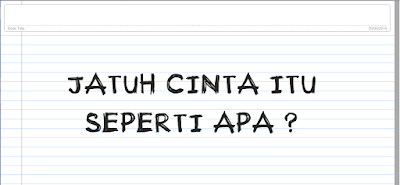Di sebuah salon
kecantikan.
Kupandangi
wajah pelangganku ini, mungkin seumuran dengan ibuku yang ada di kampung. Ah
aku sudah lama tidak pulang menengok ibu dan bapak di kampung. Tapi kalau
pulang juga pasti sangat menyebalkan, mendengarkan mereka berdua mengomelkan
banyak hal tentang dandananku. Yang katanya aku menor, aku terlihat tua dari
umurku, aku berdandan seperti perempuan tidak benar, rambutku yang ku cat merah
sepertinya sangat mencemarkan nama baik mereka di kampung. Ditambah lagi dengan
komentar mereka tentang pakaianku. Ah aku tidak mau mengingat mereka, membuat
sakit hati saja.
Padahal
tiap kali aku pulang, aku pasti tidak pernah absen membawakan duit yang bisa
memenuhi kebutuhan mereka sampai berbulan-bulan. Rumah di kampung juga bisa
diperbaiki semua berkat duit dari kerja kerasku. Tapi mereka tidak pernah
peduli, yang mereka pedulikan adalah omongan dari tetangga yang berkomentar
macam-macam tentang pekerjaanku dan pakaianku.
Mereka
harusnya tahu, aku bekerja di salon. Kalau aku tidak berdandan cantik dan
mengenakan pakaian yang tidak modis tentu pelangganku tidak akan percaya pada
keterampilanku merias wajah dan menata rambut. Ah mereka tahu apa, hanya bisa
bergosip tiap hari. Padahal di kampung mereka sangat miskin, seharusnya mereka
bekerja bukannya hanya bergosip di warung-warung makan dan di pekarangan rumah.
Muak aku, tapi aku juga tidak peduli. Sejak aku pergi ke kota, aku tahu di sini
aku harus merubah nasipku. Aku tidak ingin miskin terus, aku harus bekerja
keras. Disini tuntutannya sangat tinggi, jika ingin dihormati dan tidak
dipandang rendah, aku harus mengikuti zaman.
Pertama
adalah merubah gaya berpakaianku, lalu membeli SmartPhone dengan layar yang
lebar seperti milik teman-temanku. Aku juga ingin makan di restoran-restoran
mewah atau sekedar minum di kafe sambil berfoto selfi dengan minuman yang dari
harganya tidak mungkin untuk tetangga-tetanggaku di kampung membelinya. Masuk
di kafe-nya saja mereka pasti sudah minder. Tapi aku berbeda, aku cantik dan
aku pantas!
Semua
bisa terwujud karena laki-laki itu. Awalnya memang tidak begitu kupedulikan.
Terlebih ketika ku ingat kata-kata ibuku “Secinta apapun kamu, secantik apapun
kamu dan sepintar apapun juga kalau kamu merebut lelaki milik perempuan lain,
kamu dinamakan: binatang!” Kata ibu keras sambil melempar senyum getir, aku
menggigil. “Hanya perempuan yang tidak punya hati yang dapat melakukan itu.
Semua ada karmanya. Jangan sampai mengganggu rumah tangga orang lain.
Balasannya lebih berat!” Tambah ibu lagi, matanya menerawang entah apa yang dia
pikirkan, seolah dia tidak sedang berada ditempatnya saat ini. Aku hanya diam
tidak tahu harus berbuat apa.
Tapi
itu dulu sekali, kata-kata ibu seolah seperti tertelan segala bentuk kemewahan
yang aku miliki. Juga segala limpahan kasih sayang yang laki-laki itu berikan
untukku, dia begitu perhatian lebih dari bapakku atau laki-laki manapun. Aku
tidak pernah merasa sebegitu tersanjung ketika dia berikan bunga mawar dan
cincin. Meskipun aku dengar dari teman-teman yang lain bahwa selain punya istri
dan empat anak, laki-laki tersebut juga tidak begitu kaya. Tapi aku tidak
peduli, teman-temanku hanya iri. Yang terpenting adalah aku bisa hidup enak
sekarang, tidak hanya mengandalkan duit gaji kerja di salon yang tidak
seberapa. Aku sadar duit itu hanya akan habis untuk mengirimi bapak ibuku di
kampung saja. Sedangkan jika dari laki-laki ini aku bisa berdandan dengan
kosmetik bermerk, baju-baju bermerk dan tentu aku bisa memamerkan foto-foto
kelas atas ke sosial media yang akan membuat teman-temanku iri.

Aku
rasa semua ini juga bukan murni karena kesalahnku saja, kenyataannya istri
laki-laki itu tidak secantik aku, tentu lah suaminya mencari perempuan lain.
Istrinya itu gembrot, tubuhnya dipenuhi lemak disana-sini dan laki-laki mana
yang mau tidur dengan perempuan yang baunya selalu seperti bumbu dapur. Tidak
seperti aku yang selalu menjaga penampilan dan juga wangi. Pantaslah kalau
suaminya lebih memilih tidur denganku. Jadi jangan salahkan aku, aku memang
cantik dan langsing. Dan jika suaminya menyukai aku dengan segala kasih sayang
yang dia berikan, masak aku tolak?
Di sebuah kamar tidur.
Kupandangi
cermin di depanku, yang nampak adalah seorang perempuan dengan tubuh telanjang.
Tanpa secuil pun kain yang melekat. Kulitnya tak lagi semulus dulu, sekarang
berbagai guratan yang menandakan bekas dapur dan sumur begitu melekat. Ditambah
dengan gumpalan-gumpalan lemak disekitar paha dan perut, padahal dulu aku begitu
sintal, tidak terlalu gemuk tapi tidak terlalu kurus, pas saja dan segar. Sekarang
banyak bagian yang tidak begitu sedap dipandang. Beralih ke bagian wajah, dulu
bibir yang merah itu begitu indah, sekarang legam padahal aku tidak merokok.
Pipiku yang dulu juga bersih, tiba-tiba menjelma menjadi rawa, banyak
bercak-bercak hitam yang berkerumun menghuninya.

Ini
semua gara-gara KB! Namanya perempuan, kalau tidak pakai KB, ratusan anak bisa
lahir. Yang repot siapa? Perempuan juga. Katanya kalau pakai IUD, lebih aman.
Tapi aku takut, masak ada benda yang terbuat dari plastik dan tembaga berbentuk
T dimasukan ke dalam rahim, pemakaiannya bisa 4-5 tahun. Ketika alat itu
dipasang kita harus menaikan kaki tinggi-tinggi. Mengangkang! Yang buat aku
ngeri, kita harus memeriksa diri sendiri apakah alat kontrasepsi itu masih
berada dalam rahim dengan cara meraba benang IUD tersebut ke dalam vagina.
Ngeri kalau harus memasukan jari sendiri ke dalam vagina. (Novel Tempurung - Oka Rusmini, dengan sedikit edit).
Selain
itu, segala macam pekerjaan rumah juga aku sendiri yang mengurus tanpa
pembantu. Jangankan menyewa pembantu, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
saja aku juga harus bekerja berjualan nasi dan lauk-pauk tiap pagi. Mengurus 4
orang anak yang semuanya butuh makan. Mengurus rumah yang tiap hari selalu saja
kotor. Mencuci, memasak, menyetrika, mengepel, menyapu, bagai babu di rumah
sendiri. Kamu ingin aku tetap cantik seperti dulu? Semua tergerus perlahan
terlebih dengan pekerjaan yang mengharuskanku bekerja keras siang malam di
dapur demi menambah pemasukan tiap hari. Kamu begitu ingin aku selalu wangi?
Bau asap dapur yang akan kau cium!
Berbeda
sekali dengan kamu yang bekerja kantoran, mungkin hanya pegawai negeri
rendahan, tapi kenyataannya duit gajimu malah kamu tukar dengan mobil. Yang
harus kamu cicil dengan duit gajimu tiap bulan, hingga minus. Dan harus aku
yang memenuhi segala kebutuhan rumah perharinya, pintar sekali kamu. Jelas kamu
bisa kelihatan rapi bersih dan wangi tiap hari sehingga dapat digoda perempuan
muda di luar sana. Apalagi dengan setelan seragam pegawai negerimu, lengkaplah
untuk perempuan lain mengangapmu laki-laki sukses. Sedangkan aku hanya di
belakangmu sambil merapikan segala kegagalanmu sebagai suami.
Memang
sudah kodratnya sebagai perempuan, aku tidak ingin menyalahkan takdir. Tapi
kenapa aku yang selalu disalahkan saat suamiku ketahuan memiliki perempuan lain
di luar? Mereka menyalahkanku karena aku gembrot, tidak bisa menjaga tubuh, bau
ku seperti bumbu dapur dan selalu cerewet. Mereka juga bilang aku perempuan
goblok, yang mau saja dibohongi suaminya terus. Andai saja mereka tahu, aku
juga sakit hati tiap kali membayangkan suamiku tidur dengan perempuan lain. Pertengkaran
demi pertengkaran tiap hari, barang-barang yang dibanting ke lantai dan juga
anak-anak yang ketakutan. Aku mulai lelah dan sadar bahwa semua itu tidak ada
gunanya. Sekarang bagiku aku sudah tidak dapat egois lagi, tubuh ini sudah
bukan lagi milikku sendiri tapi juga milik anak-anakku. Banyak yang harus aku
pertimbangkan. Aku tidak ingin memberikan keluarga yang tidak utuh bagi mereka,
setidaknya saat mereka pulang sekolah mereka akan menjumpai bapak ibunya ada di
rumah.
Menjadi
seorang perempuan terlebih seorang ibu, sudah bukan waktunya lagi memikirkan
diri sendiri. Buatku melihat anak-anakku tumbuh adalah kebahagiaan yang luar
biasa, yang terpenting sekarang adalah anak-anakku. Dan suamiku? Yang penting
dia tidak membawa perempuan lacur itu ke dalam rumah tangga ini bagiku
perempuan tersebut hanya pekarangan belakang yang tidak perlu aku tahu, aku
ingin tutup mata saja soal itu. Selain itu juga suamiku tetap memikirkan
kebutuhan anak-anak, itu sudah cukup.
Di sebrang sebuah jalan
Di
pandangi teman-temanku, rasanya risih sekali. Mereka mengamati mataku yang
bengap hasil dari menangis semalaman. Aku hanya diam saat teman-teman
menanyaiku macam-macam. Beruntun!
Aku
bercerita pun mereka belum tentu akan mengerti keadaanku. Jadi aku hanya diam
saja, aku juga tidak ingin berbagi duka untuk mereka, buatku teman-teman hanya
cukup tau suka ku saja. Kenyataannya aku masih lengkap dengan tawaku dan ceria
sepanjang bersama mereka meskipun mata sepertinya tidak dapat membohongi. Tak
apalah biar semua sesak kumiliki sendiri.
Segala
hal yang begitu menyakitkan, ketika melihat kedua orang tuaku saling
membantingi barang-barang rumah, saling memaki satu sama lain. Aku yang hanya
mampu menangis terisak diam-diam, hal yang sepertinya bukan terjadi sekali dua
kali di rumah, tapi begitu sering bahkan aku lupa sejak kapan dimulainya.
Sepertinya sudah sejak aku masih kecil, aku juga lupa kapan. Entah!
Aku
hanya kadang bingung harus bagaimana saat kedua orang tuaku sudah saling memaki
satu sama lain. Berbagai perasaan tiba-tiba saja menyerbuku, membuatku seolah
menjadi patung, diam beku ditempatnya. Hanya melihat sambil air mata meleleh
dan beku sendiri.
Pernah
suatu ketika aku berharap kenapa mereka tidak bercerai saja sekalian, daripada
hanya tiap hari bertengkar terus, barang-barang di rumah pecah rusak. Apalagi
saat itu yang dibanting adalah radio kesayanganku, hanya itu hiburanku di rumah.
Tapi sampai sekarang mereka tidak bercerai juga, entah aku harus bersyukur atau
tidak bagiku semua sama saja. Mereka masih rajin perang dingin kalau sekarang.
Membuatku bingung dan ikut dingin hingga membeku di rumah.
Jadi
kuputuskan untuk pergi saja, pulang hanya sekedar untuk menengok adikku yang
terkecil yang masih sering berlarian mengikutiku kalau aku keluar rumah. Tidak
ada lagi yang peduli padaku, ibu juga hanya akan marah-marah membuat kupingku
panas, sebaliknya bapak malah hanya diam seolah aku adalah makhluk transparan
yang tidak pernah ada keberadaannya. Saat pulang aku hanya kasihan pada
adik-adikku yang masih kecil. Melihat mereka seperti melihat diriku sendiri
saat itu. Hanya menangis sesenggukan.
Kuputuskan
untuk tidak lagi peduli, entah ibu yang salah karena jelek, gendut, dan cerewet
atau kerena bapak yang punya perempuan lain di luar, atau malah si perempuan
jahat yang sudah menggoda bapak. Aku benar-benar tidak peduli, kenyataannya hanya
aku dan adik-adikku yang menjadi korbannya. Rumahku surgaku sudah tidak lagi
kami mengerti maknanya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi
kami sudah tidak lagi berfungsi. Dan aku lebih memilih panas terik matahari
sebagai tempatku berlindungku.
Kurapikan
kembali tumpukan koran yang ada disebelahku, lalu kupeluk mereka dalam dadaku
seolah mereka seperti seorang bayi yang akan terjatuh lepas satu satu kalau
tidak aman dalam pelukanku. Dari sinilah aku bisa makan tiap hari, bersama
teman-teman yang juga mencari sesuap nasi di bawah lampu merah. Diseberang
jalan kulihat bapak berlalu dengan perempuan cantik yang seumuran denganku,
begitu bahagia menaiki Avansanya.

 Tentang Malam
Tentang Malam